Artikel kali ini saya ingin membahas secara analisis fundamental mengapa pabrik tekstil besar dan terkemuka di Indonesia seperti PT. Sri Rejeki Isman (SRIL) bisa pailit. Analisis ini saya bagi menjadi 2 bagian yaitu analisis secara kuantitatif dan kualitatif.
I. Analisis Kuantitatif
Dalam melakukan analisis kuantitatif saya setidaknya menemukan 5 RED FLAG untuk SRIL ini sejak tahun 2014. Berikut penjelasannya:
1# RED FLAG (Revenue & AR)
Sebenarnya secara laporan keuangan full year dari tahun 2013-2023 masalah SRIL ini sudah mulai tampak sejak tahun 2013 ke 2014. Pertumbuhan Pendapatan (Revenue) dengan pertumbuhan piutang (account receivables/AR) angkanya sangat terpaut jauh. Lihat tabel di bawah ini:
Pertumbuhan AR yang jauh lebih cepat dibandingkan Revenue adalah hal yang berbahaya hal yang berbahaya karena perusahaan seolah-olah “borowing from the future” karena real cash-nya belum diterima oleh perusahaan. Hal ini terjadi di 2013-2014 dan berlanjut terus dari 2016-2020.
2# RED FLAG (Inventory)
Karena manajemen SRIL agresif sekali dalam mencari AR, maka imbasnya terjadi inventory build up yang pada akhirnya harus dihapus bukukan di tahun 2021 - 2022
Inventory SRIL:
Components Of Inventory:
Penumpukan inventory apabila terjadi di akun bahan baku dan didukung dengan penjualan yang meningkat maka itu sign ada pertumbuhan bisnis, tapi apabila terjadi di akun “barang jadi” dan “barang setengah jadi/dalam proses” ini bisa menjadi sumber masalah (sign of risk) di masa depan karena perusahaan kemungkinan harus melakukan bersih-bersih persediaan. Ingat persediaan bisa usang/rusak (kecuali persediaannya emas batangan). Biasanya cara paling cepat membersihkan persediaan adalah dengan memberikan diskon besar-besaran dan memberikan tempo pembayaran yang panjang terhadap customer agar mau mengambilnya. Ini yang terjadi di SRIL. Selain itu penumpukan barang jadi/barang setengah jadi juga sign akan ada perlambatan produksi di masa depan.
Hari Persediaan & Hari Piutang SRIL:
Apakah Anda dapat melihat ada permasalah penumpukan inventory dan berujung pada perpanjangan piutang sebelum permasalahan meledak di 2021-2022?
3# RED FLAG (Cash Flow)
Cash Flow SRIL juga bermasalah terutama di bagian Free Cash Flow-nya (FCF). SRIL sejak 2013 hingga 2021 sama sekali tidak pernah mencatatkan FCF positif. Penyebabnya ada kaitannya dengan red flag 1 & 2 ditambah kebutuhan capital expenditure (capex).
Lucunya SRIL ini masih bagi dividen sepanjang 2015 - 2020 walaupun FCF-nya minus. Sudah pasti dividen itu dibayar dari duit utang.
4# RED FLAG (Debt)
Debt yang saya maksud ini adalah utang berbunga. Karena hal yang paling cepat membuat perusahaan pailit adalah utang berbunganya. Gabungan dari ketiga red flag di atas menyebabkan SRIL harus menggunakan dana pinjaman agar bisnisnya dapat terus berjalan.
Debt seperti pedang bermata dua, bagaimana menilai Debt ini dipergunakan untuk pertumbuhan perusahaan atau sudah masuk kategori buruk? Saya menilainya dengan membandingkan cost of debt dengan return on asset. Mengapa demikian? Karena ketika perusahaan menerima dana dari pinjaman, maka dana tersebut akan langsung terakumulasikan ke total aset di neraca. Jadi apabila perusahaan dapat menghasilkan laba yang melebihi cost of debt-nya maka more debt is good. Sebaliknya apabila kasusnya seperti SRIL maka more debt is a death sentence.
ROA vs Cost of Debt
Selain tampak ketidakefisienan penggunaan utang SRIL (yang juga dibagikan sebagai dividen), tampak juga penurunan profitabilitas SRIL karena ROA-nya secara jangka panjang juga menurun.
5# RED FLAG (Management Salary & Remuneration)
Perusahaan performa secara gradual memburuk tapi manajemennya mengambil gaji yang naik terus tiap tahun relatif terhadap operating expenditure-nya:
Top level management-nya baru turun gaji waktu covid-19. Sebelumnya walaupun kondisi perusahaan makin buruk tapi gajinya naik terus. Kepentingan pemegang saham publik dengan owner sudah tidak align disini.
6# RED FLAG (Net Current Asset Per Share/NCAV)
Risiko terbesar berinvestasi di saham adalah perusahaan yang kita miliki sahamnya berujung pailit. Karena nilai uang kita menjadi 0. Jadi Red Flag yang terakhir ini tujuannya untuk menjawab pertanyaan berikut:
“Apabila tesis investasi kita semula salah besar dan perusahaan akhirnya pailit, apa yang tersisa untuk investor publik?”
Maka dari itu saya menghitung berapa NCAV SRIL. Formulanya simple: (total aset lancar – total liabilitas) / jumlah saham beredar. Formula tersebut dapat Anda modifikasi dengan memasukkan juga aset tidak lancar namun harus dikurangi karena nilai yang tercatat dalam neraca sudah pasti berbeda dengan nilai saat aset tersebut di lelang. Namun untuk mempermudah saya pakai formula yang simple saja seperti di atas.
Jadi SRIL ini tidak akan menyisakan apapun kepada kita investor publik jika nanti pailit.
II. Analisis Kualitatif
Sebelum melakukan analisis kualitatif ada baiknya membaca dan mendalami perusahaan yang akan di analisis sehingga tahu mendetail bagaimana proses bisnisnya. Saya tidak akan menjelaskan proses bisnis SRIL disini untuk mempersingkat artikel ini. Jadi silakan pembaca yang belum tahu SRIL ini perusahaan apa untuk membaca-baca terlebih dahulu annual report, website, news, atau apapun itu terkait SRIL.
Dalam melakukan analisis kualitatif saya biasanya lebih suka menggunakan tools 5 Keunggulan Bersaing Porter karena dengan mempelajari dari kelima aspek yang ada dalam diagramnya dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap apa saja keunggulan bersaing dari bisnis perusahaan.
Ada 5 elemen yang harus dipertimbangkan untuk melihat kekuatan sebuah bisnis menurut Michael E. Porter. Secara singkat bagaimana kelima elemen tersebut dalam bisnis SRIL?
1. Ancaman Pendatang Baru (New Entrants)
Barrier of entry: Di Indonesia, industri tekstil ini memiliki hambatan masuk yang besar karena termasuk industri yang capital intensive dengan return bisnis yang kurang menarik. Selain itu industri tekstil bukan tipe industri yang bisa 100% otomatisasi, membutuhkan banyak tenaga kerja (padat karya). Hal ini menjadikan economies of scale menjadi barrier of entry yang tinggi bagi pendatang baru.
2. Daya Tawar Pemasok (Bargaining Power of Suppliers)
Ketergantungan Bahan Baku: Industri tekstil sangat tergantung pada bahan baku seperti kapas dan bahan kimia untuk pencelupan, yang banyak diimpor. SRIL mungkin memiliki negosiasi dalam pembelian karena volumenya yang besar, tetapi memiliki ekposur yang besar terhadap fluktuasi harga bahan baku dan juga dollar (sekitar 90% kapas yang digunakan di industri tekstil di Indonesia sumbernya dari impor). Secara diversifikasi pemasok sebenarnya SRIL ini bagus karena setahu saya memiliki banyak pilihan pemasok. Ketergantungan hanya pada satu atau sedikit pemasok membuat daya tawar perusahaan menjadi lemah karena sangat tergantung pada pemasok yang sedikit itu. Namun sayangnya karena kondisi keuangannya yang buruk, maka daya tawar ke pemasok menjadi kecil. Secara substitusi bahan baku juga setahu saya tidak banyak pilihan untuk industri tekstil seperti SRIL.
3. Daya Tawar Pembeli (Bargaining Power of Buyers)
Pembeli Utama SRIL: Sebagian besar kosumen SRIL berasal dari kalangan bisnis (B2B) termasuk sektor militer dan pemerintahan, serta merek-merek fashion besar. Produk tekstil sulit memiliki added value karena tidak ada diferensiasi yang signifikan yang dapat memberikan pricing power. Selain itu adanya persaingan global dengan negara seperti Thailand, Vietnam, India, bahkan China yang juga menawarkan produk tekstil berkualitas dengan harga yang sangat kompetitif semakin membuat SRIL tidak memiliki bargaining power to customer.
4. Ancaman Produk Pengganti (Threat of Substitutes)
Secara produk alternatif sebenarnya antar ada atau tidak. Ada tekstil berbahan sintetis dan alternatif ramah lingkungan seperti tekstil daur ulang atau berbasis serat bambu. Beberapa alternatif ini juga lebih murah atau memiliki keunggulan yang berbeda seperti tahan air atau tidak bisa kusut. Namun menurut saya posisinya tidak sampai mengganggu produk dari SRIL. Jadi walaupun ancaman dari produk substitusi ini ada namun tingkatnya masih rendah. Tidak seperti misalnya substitusi di industri jasa transportasi yang membuat konsumen dapat memilih antara pesawat, kerata api, bus, travel, dll.
5. Persaingan Antar Perusahaan Dalam Industri (Industry Rivalry)
Industri tekstil amat sangat kompetitif terutama dari produsen-produsen dari China, Thailand dan Vietnam. Hal ini memaksa SRIL untuk terus menekan biaya produksi sambil menjaga kualitas. Sayangnya tenaga kerja murah di Indonesia ini kalah dengan negara tetangga tersebut yang membuat posisi SRIL ini jadi buruk.
Kesimpulan:
Dari kelima aspek tersebut SRIL hanya menang di barrier of entry yang lumayan tinggi tapi dengan alasan yang konyol yaitu return-nya rendah makanya tidak ada pendatang baru yang mau nimbrung untuk bisnis tekstil dan ancaman produk substitusi, ya siapa yang mau pakai baju dari daun? Namun, himpitan bargaining power dari kedua sisi ini menjadi buah simalakama bagi SRIL (COGS naik, tapi jualan ga bisa naik). Jadi apabila SRIL ini ingin menang bersaing karena produknya tidak memiliki pricing power, maka satu-satunya cara harus menjadi perusahaan dengan biaya terendah sehingga SRIL harus mengoptimalkan efisiensi yang sayangnya hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena tidak mungkin bisa lebih efisien dengan pabrikan kompetitor dari China. Secara regulasi sepertinya pemerintah juga tidak berusaha melindungi industri tekstil dalam negeri. Toh walaupun dilindungi, SRIL ini penjualannya juga banyak ke mancanegara daripada domestik (komposisinya sekitar 60/40 – 70/30 lebih banyak ekspor), di mancanegara ini juga tidak mungkin pemerintah negara lain melindungi SRIL. Jadi tetap saja SRIL ini di hajar penjualannya.
Bagaimana prospek kedepan? Terus terang saya masih sulit membayangkannya. Mungkin ada yang punya pandangan lain?
Thanks for reading…








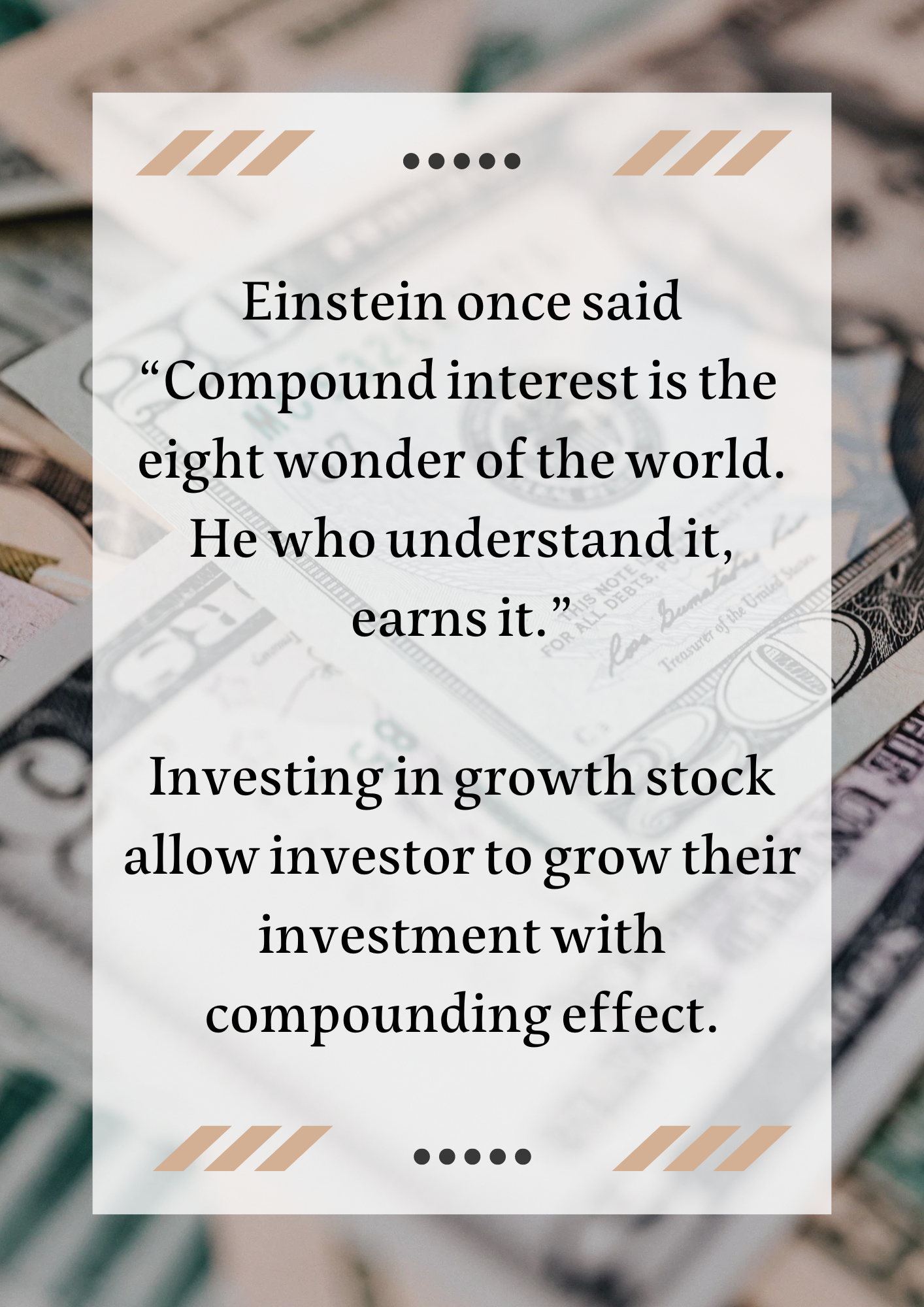
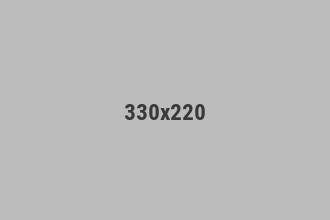

.png)



